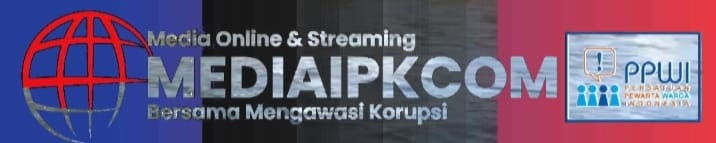Dahulu, wartawan itu semacam imam di ruang publik. Ia bicara di atas altar kata-kata yang dijaga disiplin dan rasa malu. Ia tak bisa sembarangan. Ia belajar. Ia diuji. Ia ditimbang. Ia menyadari: setiap kalimat adalah pernyataan tanggung jawab. Maka ia pun menjaga jarak dengan kabar bohong, dengan sensasi, dengan dorongan untuk tampil lebih cepat ketimbang akurat.
Wartawan, seperti dukun kampung yang memelihara reputasi dari mulut ke mulut, bergantung pada kepercayaan. Bukan hanya dari redaksinya. Tapi dari publik yang percaya bahwa apa yang ia tulis melewati saringan: kode etik, verifikasi, bahkan—jika perlu—keraguan. Ia adalah sakral bukan karena suci, tetapi karena ia sadar ia tak suci.
Tapi waktu tak tinggal diam. Seperti mesin cetak yang menggusur penyalin tangan, dunia digital mengubah medan tempur.
Kini, siapa saja bisa meliput. Semua orang bisa menjadi “jurnalis”. Ada yang mencatat peristiwa, ada yang menyiarkan aib, ada yang—bahkan—memainkan berita seperti wayang. Mereka tak perlu ruang redaksi. Tak perlu konferensi pers. Tak perlu kartu pers. Mereka cukup punya gawai dan sinyal. Lalu menjelma jadi saksi, komentator, sekaligus pelaku.
Itu yang mereka sebut citizen journalism—jurnalisme warga. Sebuah istilah yang terdengar agung, namun juga kabur. Seakan-akan dengan mengunggah video kecelakaan, seseorang telah menyelesaikan tugas jurnalistiknya. Padahal, wartawan bukan hanya soal menyampaikan. Ia soal memilih. Soal merangkai. Soal memikul beban.

Jurnalisme warga adalah kebebasan, tapi juga kekacauan. Ia seperti pasar malam tanpa lampu: ramai, gaduh, tapi penuh jebakan. Kita tak tahu mana suara, mana gema. Mana fakta, mana reka.
Namun bukan berarti kita bisa memutlakkan masa lalu. Wartawan pun pernah tergelincir. Menjadi corong kekuasaan. Menjadi juru bicara iklan. Menjadi alat yang menyamar sebagai alat ukur. Dan kini, dengan runtuhnya tembok antara wartawan dan warga, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam: siapa yang berhak bicara?
Jawabannya mungkin tak lagi tunggal. Dunia telah berubah. Tapi barangkali, kita tak perlu terlalu cemas pada perubahan itu. Sebab yang sakral bukan profesinya. Yang sakral adalah etikanya. Bukan gelarnya, tapi niat dan kehati-hatiannya.
Di tengah arus deras opini, fitnah, dan “konten viral”, masih ada mereka yang belajar membedakan suara nurani dan gemuruh likes. Mereka yang menulis bukan untuk menang, tapi untuk menerangi. Tak penting apakah mereka pernah duduk di ruang redaksi, atau hanya di meja dapur sambil mengetik di ponsel. Jika mereka tahu bahwa kebenaran tak bisa dipelintir dan manusia tak boleh direduksi jadi data klik—mereka adalah wartawan, dalam makna yang paling purba.
Dan makna yang purba itu, justru yang paling abadi.
#oleh: Ali Syrif
205 total views, 2 views today